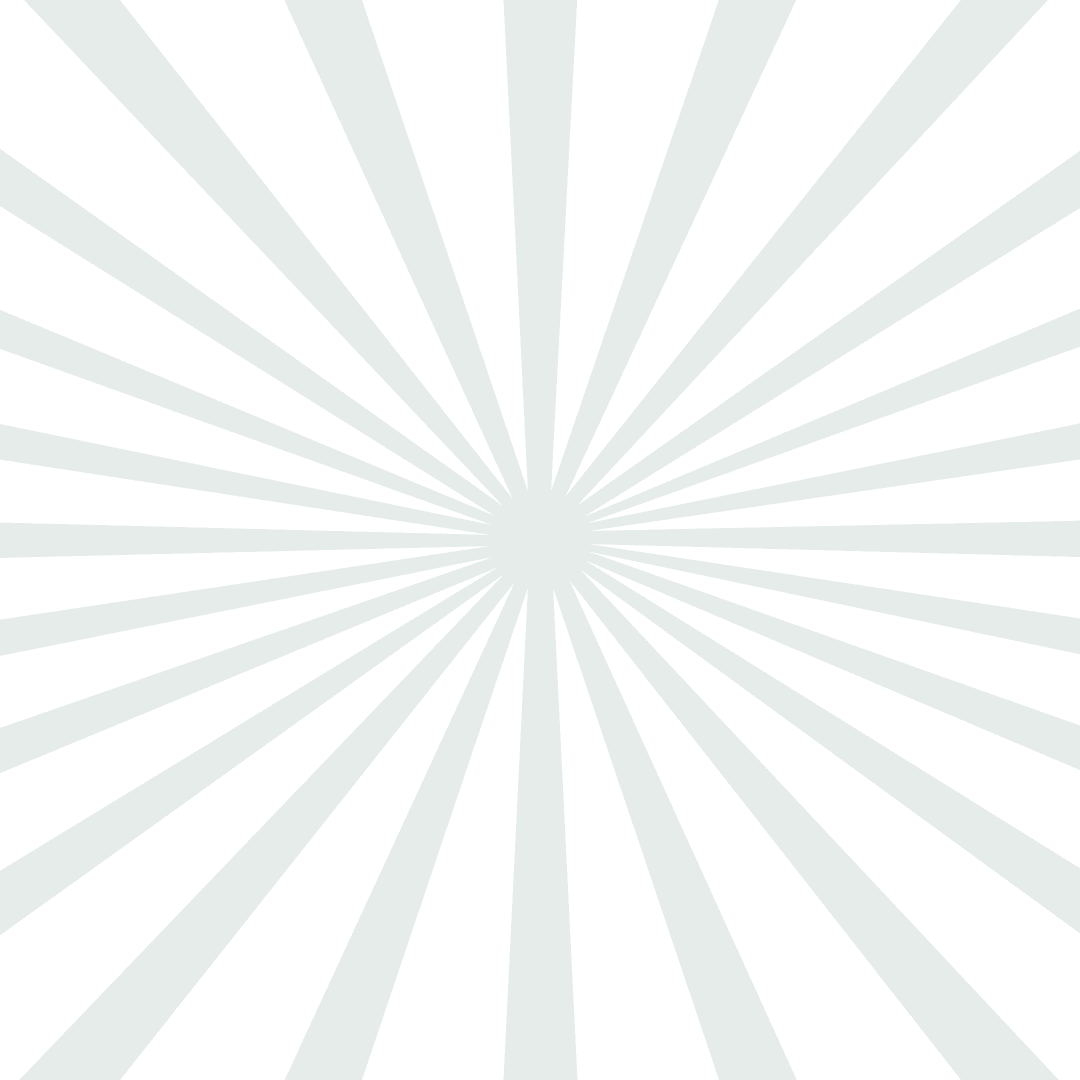Menjelang libur panjang semester sekolah atau perkuliahan, destinasi wisata selalu menjadi tujuan untuk berlibur.
Mendaki gunung menjadi salah satu kegiatan yang banyak dipilih oleh generasi muda untuk menyalurkan hobi jelajah alam.
Pertengahan Mei hingga awal Juni adalah waktu yang tepat untuk mendaki gunung karena suhu yang dingin.
Prakirawan Cuaca BMKG, Bagas Briliano, menjelaskan bahwa kondisi ini disebabkan oleh minimnya tutupan awan.
Sebelum melakukan pendakian, penting untuk memahami medan dan sejarah gunung yang akan didaki guna memastikan pendakian yang aman.
Salah satu gunung yang menjadi favorit para pendaki adalah Gunung Kelud.
Kelud adalah nama modern untuk gunung berapi yang terletak di Kabupaten Blitar, Kediri, dan Malang. Dahulu, gunung ini dikenal dengan nama “Kampud”.
Nama tersebut tercatat dalam Nāgarakṛtāgama (1365 M) dan Tantu Panggelaran (abad ke-14 M). Kampud merupakan gunung berapi yang meletus hebat pada tahun 1334 M, bertepatan dengan kelahiran Hayam Wuruk.
Lalu, apakah Kampud sama dengan Kelud?
Jawabannya ditemukan dalam kitab Tantu Panggelaran, yang menggambarkan kosmologi sejumlah gunung di Jawa Timur sebagai pecahan puncak Meru (Himalaya) yang dipindahkan dari Jambudwipa (India) ke Jawadwipa (Pulau Jawa).
Pecahan tersebut, dari barat ke timur, menjadi gunung: (1) Katong – nama kuno Gunung Lawu, (2) Wilis, (3) Kampud, (4) Kawi, (5) Arjuna, (6) Ardhi Kumukus – nama kuno Gunung Welirang.
Dalam daftar ini, Kampud disebut setelah Wilis dan sebelum Kawi. Pada kenyataannya, gunung yang terletak di antara Wilis dan Kawi adalah Kelud.
Oleh karena itu, tidak diragukan bahwa Kampud adalah nama kuno dari “Kelud”.
Tidak diketahui secara pasti kapan nama “Kelud” mulai digunakan, namun kemungkinan terjadi sejak atau setelah abad ke-15 M.
Sebagai gunung suci, gunung berapi ini dijadikan arah orientasi bagi bangunan-bangunan suci di lereng dan lembahnya.
Di puncaknya, terdapat dewa yang disebut “Bhattara Palah” dalam prasasti Palah (1119 Saka = 1197 M).
Candi Palah, yang kini dikenal sebagai “Candi Panataran”, adalah tempat pemujaan Gunung Kelud. Jika informasi dari prasasti Palah dibandingkan dengan Nāgarakṛtāgama (LXXVIII.2) yang menyebut tempat itu sebagai pemujaan Sang Hyang Acalapati, maka kedua nama tersebut (Bhattara Palah dan Sang Hyang Acalapati) merujuk pada dewa yang sama, yang diyakini bersemayam di puncak Kampud.
Oleh karena itu, wajar jika orientasi Candi Palah mengarah ke puncak Kampud. Menurut Pigeaud (1962, IV: 163), Candi Palah bukan hanya tempat dharma haji, tetapi juga sīma untuk “kaśaiwaguruan”.
Jika benar demikian, berarti latar belakang religiusnya adalah Hindu-Śiwa, sehingga Bhattara Palah (Sang Hyang Acalapati) tidak lain adalah Dewa Śiwa sebagai “Raja Gunung (Girinatha)” (Cahyono 2010).
Ada relevansi antara latar vulkanologis Kelud sebagai gunung berapi dengan Dewa Śiwa sebagai dewa perusak, karena salah satu dampak alami dari gunung berapi adalah kerusakan dan penghancuran.
Justru karena sifat destruktif ini, pemujaan terhadap dewa yang bersemayam di puncak Kelud menjadi penting, agar manusia terhindar dari bencana alam dan sebaliknya mendapat berkah.
Gunung Kampud (Kelud) memadukan maknanya sebagai gunung suci (holy mountain) dan gunung berapi (volcano).
Dualitas fungsi sebagai penumpah bencana dan pemberi berkah ini menjadikan Kampud penting bagi para pemukim di lereng dan lembahnya, yang sebagian besar adalah warga Kabupaten dan Kota Blitar.
Gunung Kelud tidak hanya menjadi simbol spiritual dan petualangan yang menantang, tetapi juga memainkan peran vital dalam keberlangsungan perkebunan di lereng-lerengnya.
Menurut sebuah penelitian, erupsi Gunung Kelud pada tahun 2014 membawa dampak positif khususnya pada potensi lahan terdampak.
Dampak ini terutama dirasakan oleh perkebunan di lereng gunung, termasuk perkebunan Karanganjar.
Selain itu, kualitas tanah di kawasan agroforestri di sekitar Gunung Kelud lebih cepat membaik pascaletusan dibandingkan lahan pertanian.
Perkebunan Karanganjar sendiri memiliki sejarah yang panjang dan penting dalam ekonomi Indonesia.
Didirikan pada tahun 1874 oleh H. J. Velsink dan Hendrik Van Vredenberg selama era kolonial Belanda, perkebunan ini kemudian dikelola oleh perusahaan Belanda, NV. Kultuur Mij Karanganjar.
Selama puluhan tahun, perkebunan ini menghasilkan komoditas kopi yang berkualitas tinggi dan menjadi bagian penting dari perekonomian lokal.
Dengan demikian, Gunung Kelud dan perkebunan Karanganjar bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam Indonesia, tetapi juga berperan penting dalam sejarah dan ekonomi negara ini.
Mari kita hargai dan jaga keberlanjutan ini untuk generasi mendatang.