Di tengah perkembangan teknologi, kesenian wayang tetap memainkan peran penting terutama dalam menanamkan nilai-nilai karakter kepada generasi muda.
Contohnya, di wilayah Blitar, para seniman pelestari wayang terus menghidupkan kesenian ini.
Meskipun dihadapkan pada beragam tantangan, kesadaran tentang pelestarian tradisi adiluhung tetap harus diperkuat agar kekayaan budaya ini terus hidup di era modern.
Salah satu inovasi dalam dunia wayang adalah Wayang Wali, yang dikembangkan oleh Ki Sudrun dari Kabupaten Blitar.
Wayang Wali ini memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari jenis-jenis wayang lainnya. Pertama, nama wayang ini berbeda dengan yang lain.
Kedua, bahan pembuatan wayang ini bisa berupa kulit atau kayu (seperti dalam wayang golek) dengan tokoh-tokoh cerita yang berbeda.
Ketiga, cerita yang dibawakan tidak selalu mengikuti pakem tradisional, seperti dalam pertunjukan dengan judul “Tanpa Lakon”.
Keempat, lagu-lagu yang dilantunkan dalam Wayang Wali tidak terbatas pada tembang Jawa saja, tetapi juga mencakup lagu-lagu Islami yang berisi pujian dan doa kepada Tuhan.
Kelima, alat musik yang digunakan untuk mengiringi pertunjukan ini terdiri dari kombinasi gamelan Jawa, alat musik modern seperti gitar, keyboard, dan drum, serta terbang.
Karakteristik fisik Wayang Wali dengan judul “Tanpa Lakon” dapat dilihat dari bahan, warna, tampilan, dan hubungan tampilan wayang dengan karakter yang diwakili.
Wayang Wali terbuat dari kulit dan kayu, dan pembuatan wayang kulitnya dilakukan oleh Pak Djoko, seorang pengrajin wayang yang mampu merealisasikan ide-ide Ki Sudrun.
Persiapan untuk pementasan biasanya dimulai empat bulan sebelumnya, di mana Ki Sudrun menuliskan tema dan alur cerita.
Setiap warna pada Wayang Wali memiliki makna tersendiri. Warna merah melambangkan nafsu, putih melambangkan kebijaksanaan, warna kuning melambangkan ketentraman, dan warna hitam digunakan sebagai simbol kejantanan atau keganasan.
Dalam pementasan, warna merah digunakan untuk tokoh antagonis seperti yaksa, raksasa, hewan, setan, dan penjahat, sedangkan warna kuning, putih, dan coklat digunakan untuk tokoh protagonis seperti punokawan, sunan, raden, kyai, dan rakyat jelata.
Kombinasi warna kuning dan merah sering digunakan untuk mewakili tokoh-tokoh seperti mucikari, tuna susila, dan pejabat yang terkena kasus.
Dalam pementasan Wayang Wali, tiga bentuk gunungan digunakan: gunungan kaligrafi, gunungan lubang, dan gunungan pasujudan.
Gunungan kaligrafi berisi ornamen kaligrafi dengan kalimat syahadat, gunungan pasujudan menggambarkan kesadaran untuk berserah diri kepada Tuhan saat menghadapi cobaan, sering dimainkan dengan gunungan lubang di atasnya untuk melambangkan dunia.
Amanat dalam Wayang Wali banyak mengandung ajaran moral serta nilai-nilai perilaku baik dan buruk menurut ajaran Islam dan falsafah Jawa.
Ki Sudrun menggunakan wayang sebagai media dakwah, tetap berkontribusi pada kebudayaan.
Amanat dalam pementasan “Tanpa Lakon” meliputi: (a) manusia dilahirkan dengan cipta, rasa, dan karsa, sehingga harus memiliki sifat terpuji agar masuk surga dan dijauhkan dari neraka, (b) setiap anak harus menghormati ibu, (c) manusia diharapkan menata hidup sesuai akhlak, tata krama, dan norma yang baik untuk menyeimbangkan urusan lahir dan batin, (d) manusia harus bersatu meskipun memiliki kepentingan berbeda, dan (e) manusia hendaknya berusaha dan tidak hanya pasrah pada kodrat.
Amanat-amanat ini tercermin dalam berbagai peristiwa dalam cerita, seperti pencarian pohon aren dan kolang-kaling oleh Raden Said dan Brandal Lokajaya, serta wejangan Semar kepada Bagong, Petruk, dan Gareng.
Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam wayang wali dengan cerita “Tanpa Lakon”, tema yang diambil adalah peperangan, tetapi bukan dalam arti fisik.
Peperangan yang menjadi fokus dalam Wayang Wali adalah perang batin manusia melawan hawa nafsu untuk kembali kepada ajaran Allah. Ini mencerminkan adanya akulturasi antara budaya Jawa dan budaya Islam.
Unsur budaya Jawa tetap dipertahankan dengan mengangkat tema peperangan, namun dipadukan dengan nilai-nilai Islam, yaitu peperangan melawan hawa nafsu.
Dalam pandangan spiritual orang Jawa, manusia memiliki empat nafsu: amarah, luamah, supiyah, dan mutmainah.
Dalam cerita wayang, karakter-karakter tertentu mencerminkan sifat-sifat tersebut.
Akulturasi dengan Islam terlihat dalam bagaimana semua nafsu tersebut diarahkan untuk kembali kepada ajaran Allah.
Selain wayang wali, akulturasi Islam dengan budaya Jawa juga terlihat pada tradisi kenduri di acara Tradisi Manten Kopi yang dilaksanakan setiap tahun di De Karanganjar Koffieplantage sebagai penanda musim panen raya tiba.
Tradisi kenduri biasanya dipimpin oleh pemuka adat atau tokoh masyarakat di lingkungan yang bersangkutan.
Dalam kenduri, sajian utama biasanya berupa tumpeng lengkap dengan lauk-pauk.
Makanan ini kemudian dibagikan kepada para hadirin sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk menjaga tali silaturahmi antarwarga masyarakat.
Kenduri juga berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk merawat keutuhan dan meneguhkan kembali cita-cita serta tujuan bersama.


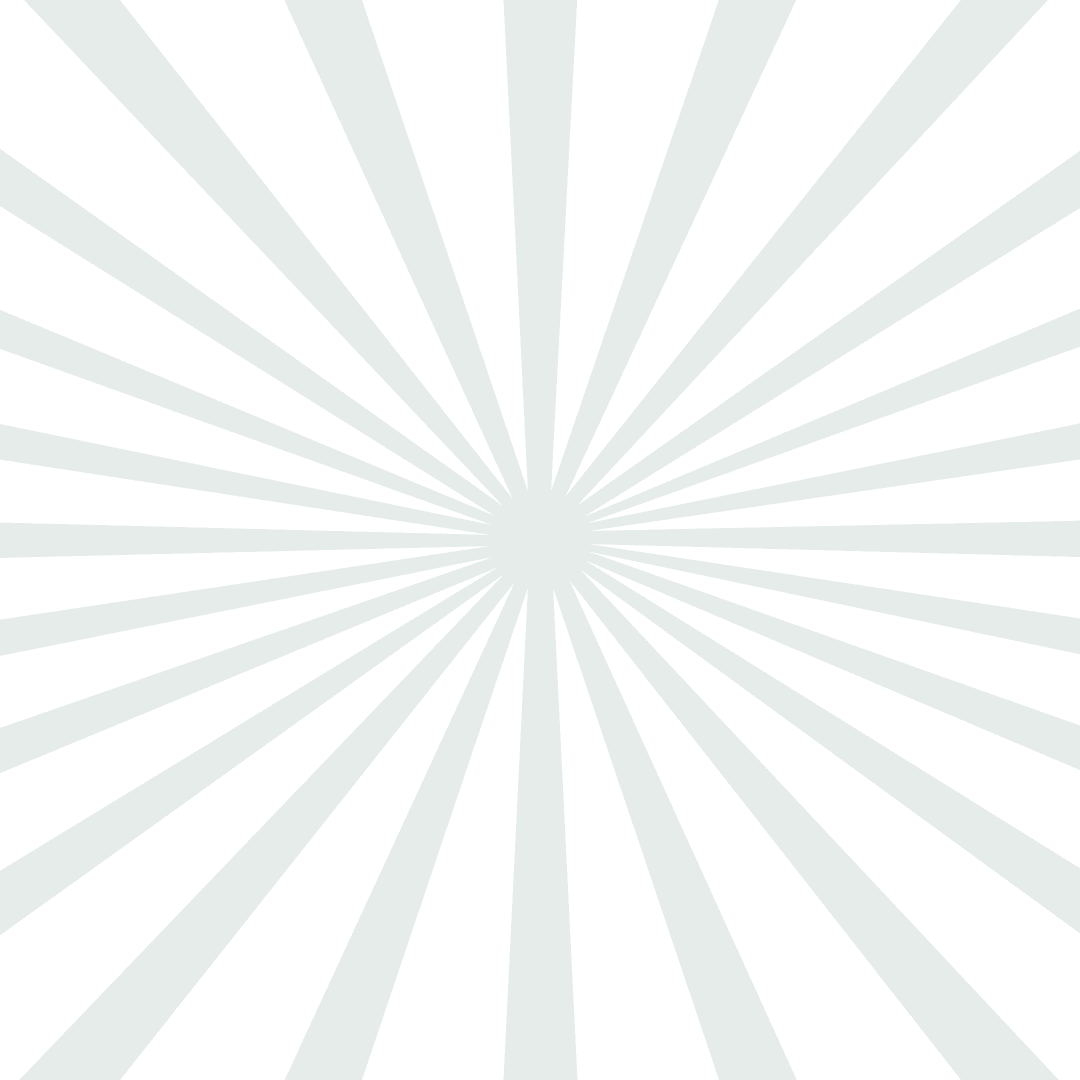





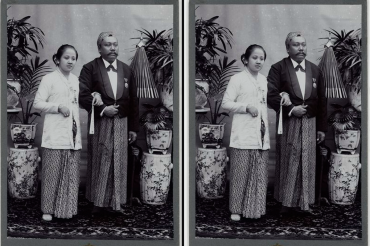

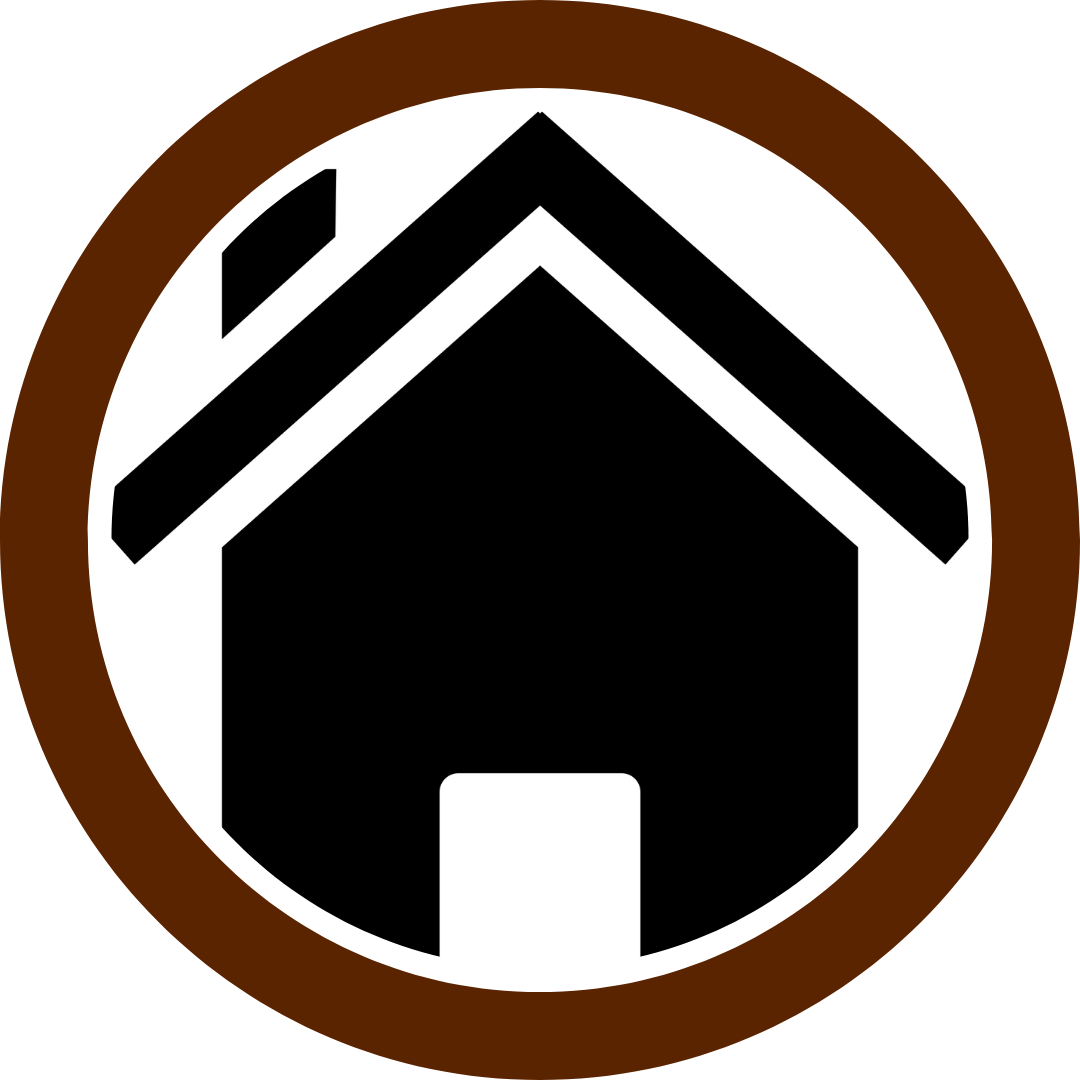 Home
Home
 IG
IG
 Tiktok
Tiktok
 Shopee
Shopee
 Chat
Chat