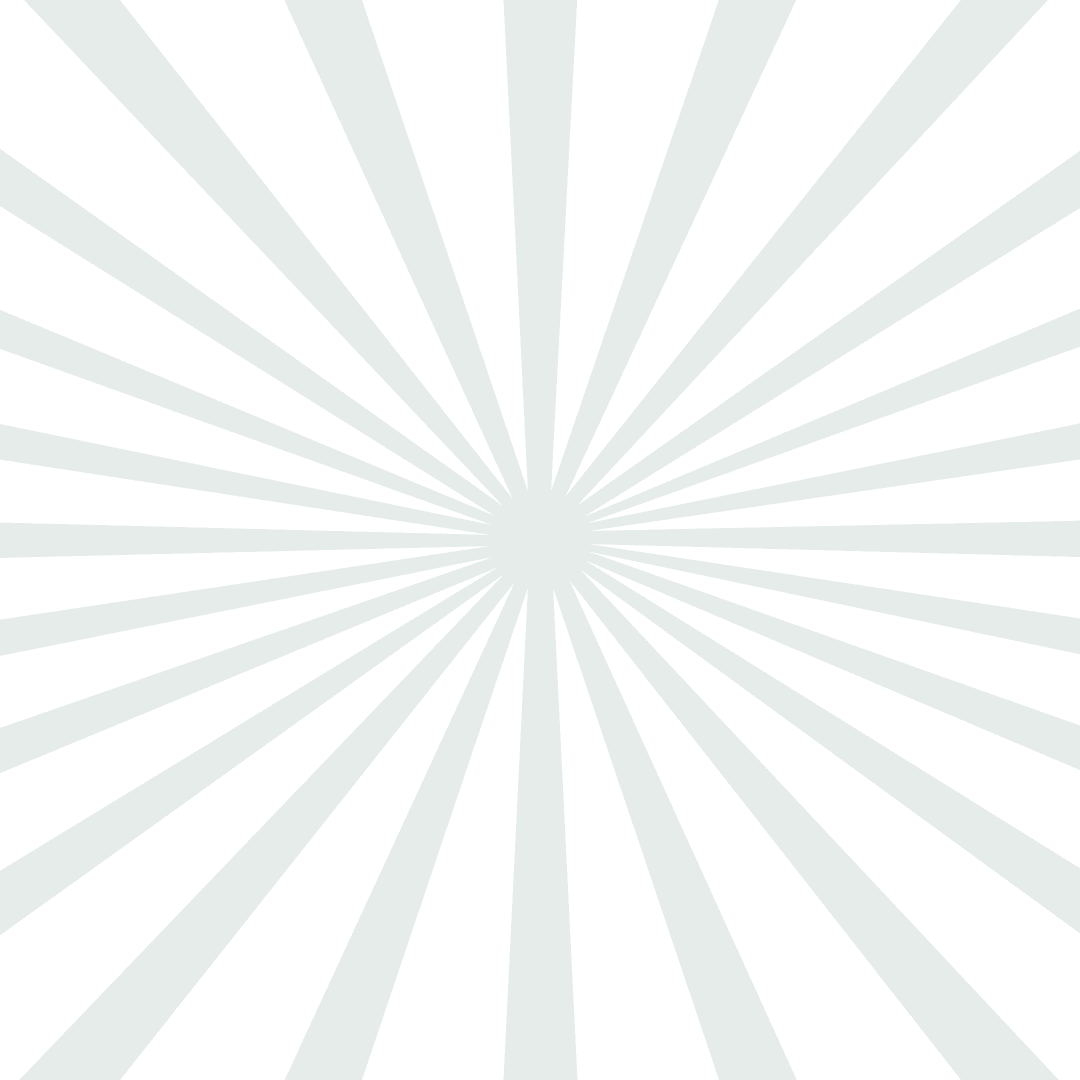Pada paruh kedua abad ke-19, situasi politik di Belanda mengalami perubahan signifikan dengan meningkatnya pengaruh kaum liberal.
Kaum liberal ini berjuang untuk mendapatkan peluang yang lebih luas dalam aktivitas dan pengelolaan ekonomi di tanah jajahan.
Mereka berpandangan bahwa pemerintah Belanda tidak akan mampu menangani berbagai persoalan yang kompleks dan luasnya wilayah jajahan sendirian.
Oleh karena itu, mereka menginginkan kesempatan untuk menginvestasikan modal mereka dalam berbagai usaha ekonomi di tanah jajahan serta mengelola daerah tersebut agar persoalan yang timbul dapat segera ditangani dengan baik, serta tetap memberikan keuntungan optimal bagi Belanda.
Di Blitar, daerah yang memiliki potensi ekonomi besar, perkebunan-perkebunan besar mulai dibuka di sekitar lereng Gunung Kelut di Blitar Utara dan sepanjang lembah aliran Sungai Brantas hingga Blitar Selatan.
Investasi modal swasta di Blitar mampu membantu memenuhi kebutuhan bahan mentah seperti karet, coffee, kakao, tebu, dan tembakau untuk pasar Eropa, serta kapas, serat nanas, kelapa, kina, teh, singkong, dan cengkeh.
Blitar menjadi pusat aktivitas ekonomi yang sangat penting bagi Belanda, dengan banyaknya hasil perkebunan yang diekspor ke pasar internasional.
Industrialisasi di tanah jajahan, terutama di Blitar, menghasilkan produk-produk yang laku di pasaran dunia, khususnya Eropa.
Untuk mendukung ekspor dari Hindia Belanda, Belanda membangun berbagai fasilitas seperti pelabuhan besar di Batavia, Semarang, Surabaya, dan Makassar.
Meskipun Blitar berhasil memproduksi berbagai komoditas unggulan dalam jumlah besar, daerah ini tidak memiliki pelabuhan ekspor sendiri karena letaknya di pedalaman dan akses geografis yang sulit.
Untuk mengatasi hal ini, komoditas dari Blitar diangkut ke pelabuhan-pelabuhan yang memiliki akses ekspor, yang memerlukan pembangunan sarana perhubungan dan transportasi yang memadai.
Belanda membangun jalan raya yang menghubungkan Blitar dengan daerah-daerah lain dan pelabuhan-pelabuhan utama. Jalan ini menghubungkan Blitar dengan Tulungagung, Kediri, dan Malang, yang kemudian terhubung ke Surabaya.
Kondisi medan yang berbukit dan terjal, serta daerah aliran lahar erupsi Gunung Kelut, menjadi tantangan besar dalam pembangunan ini.
Infrastruktur jalan raya ini tidak hanya digunakan untuk keperluan ekspor, tetapi juga untuk memperlancar mobilitas manusia, barang, dan jasa antardaerah.
Pembangunan jalan raya yang menghubungkan Blitar dengan daerah-daerah sekitarnya memerlukan kerja keras dan perencanaan yang matang untuk mengatasi tantangan geografis.
Selain jalan raya, kereta api juga menjadi alternatif penting yang diperhatikan oleh Belanda untuk membuka isolasi Blitar dan memfasilitasi angkutan penumpang dan barang.
Pembangunan jalur kereta api dari Kediri ke Blitar dimulai pada 1881 dan diresmikan pada 1884, memperlancar pengangkutan komoditas ekspor dari Blitar ke Surabaya.
Jalur ini kemudian diperpanjang ke arah Malang untuk memperlancar ekspor dan mobilitas barang serta manusia.
Pembangunan jalur kereta api dari Blitar ke Malang dilakukan lebih belakangan karena medan yang lebih berat dan pekerjaan yang memakan waktu lebih lama.
Jalur ini harus menembus daerah perbukitan terjal dan sungai besar, yang menambah tantangan dalam pembangunannya.
Pembangunan ini didorong oleh potensi industri pertanian di Blitar, terutama perkebunan coffee di Wlingi. Modernisasi transportasi dengan adanya jalur kereta api memudahkan perpindahan barang, manusia, dan uang, serta memicu perkembangan kota Blitar.
Selain infrastruktur transportasi, Belanda juga membangun gudang penyimpanan komoditas di Blitar, dekat stasiun kereta api dan di kompleks kantor besar perkebunan (De Lennepstraat).
Gudang-gudang ini digunakan untuk menyimpan berbagai jenis produk perkebunan sebelum diangkut ke luar daerah atau diekspor.
Proses penyimpanan ini melibatkan pengeringan dan penanganan khusus lainnya untuk memastikan produk siap dikirim.
Gudang besar di GemeenteBlitar menjadi pusat transit barang yang akan diangkut ke luar daerah atau diekspor.
Setiap perkebunan dan perusahaan pengolahan memiliki gudang penyimpanan sendiri di lokasi perusahaannya atau di dekat perusahaan tersebut.
Seluruh hasil panen perkebunan diproses dan disimpan sementara di gudang perusahaan atau perkebunan, sebelum diangkut ke gudang besar di Gemeente Blitar.
Namun, perkembangan perkebunan di Blitar mengalami kemunduran pada 1930-an akibat krisis ekonomi global yang dikenal sebagai krisis malaise.
Krisis ini menyebabkan banyak negara dan perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang serius. Banyak perkebunan yang gulung tikar atau diambil alih oleh perusahaan yang lebih besar, mengurangi jumlahnya menjadi 45 perusahaan pada 1939.
Sebagian perusahaan yang menghadapi masalah keuangan atau bangkrut kemudian dijual kepada pihak lain atau dimerger dengan perusahaan lain.
Seleksi alam dan persaingan yang ketat mengakibatkan banyak perusahaan kecil tidak mampu bertahan.
Salah satu perkebunan yang tetap bertahan hingga masa nasionalisasi adalah Perkebunan Karanganjar, yang menjadi contoh keberhasilan investasi swasta dalam mengelola dan memanfaatkan potensi ekonomi di tanah jajahan.
Perkebunan Karanganjar menjadi simbol keberlanjutan dan adaptasi dalam menghadapi tantangan ekonomi yang berat.