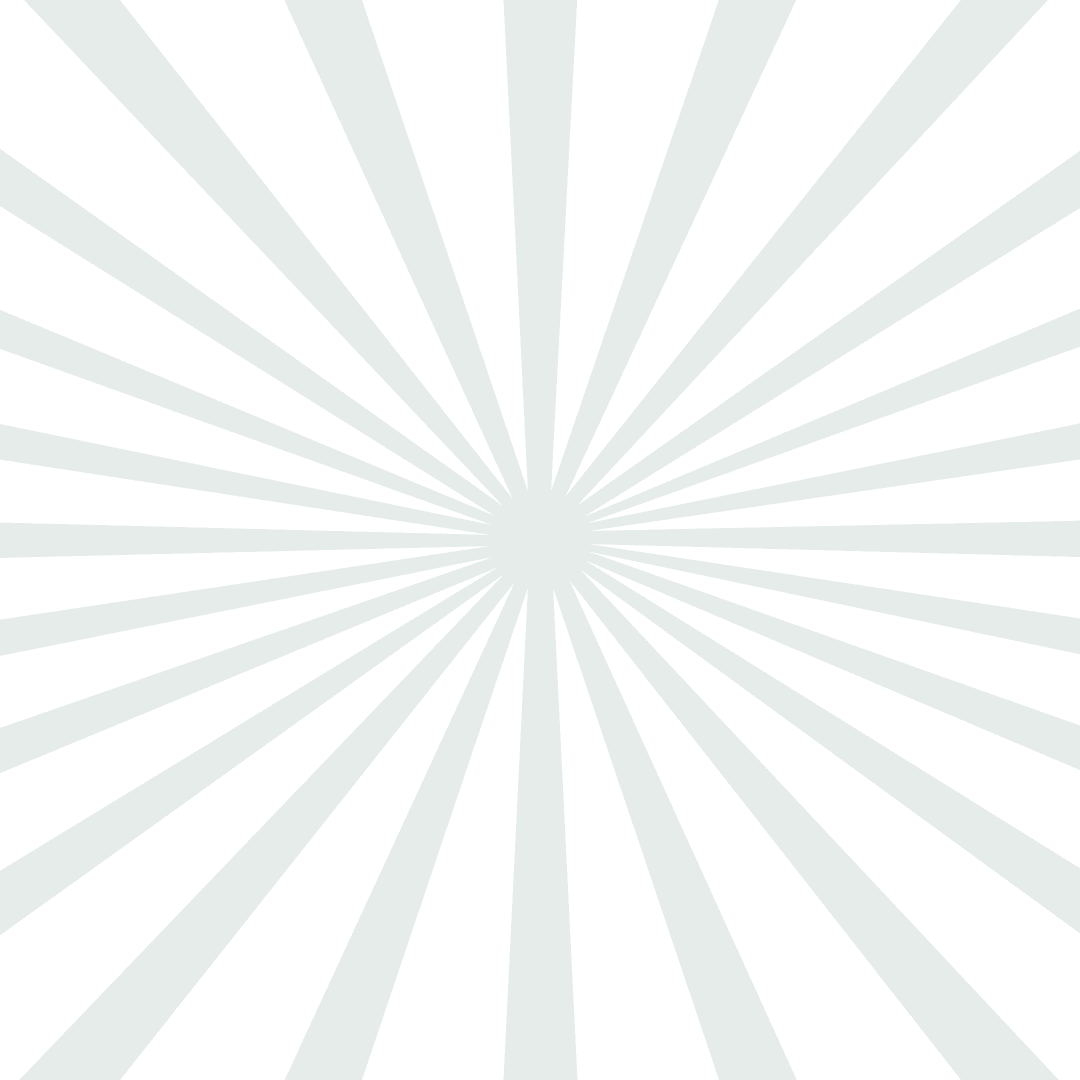Kemenangan politik kaum liberal di Parlemen Belanda pada tahun 1870 memicu lahirnya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula.
Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk memperluas kesempatan investasi dan memperkuat ekonomi kaum borjuis di Belanda.
Dengan meningkatnya jumlah modal yang dimiliki, mereka mulai berfokus pada ekspansi usaha di wilayah jajahan, seperti di Indonesia.
Kepentingan ekonomi kaum borjuis ini mendapat dorongan kuat dari menyebarnya ideologi liberalisme di Belanda, yang menekankan kebebasan pasar dan meminimalkan intervensi negara dalam ekonomi.
Penerapan undang-undang tersebut dan semakin dominannya pengaruh liberalisme mengakibatkan berkembangnya perusahaan perkebunan dan pertambangan besar di Jawa dan Sumatra.
Perusahaan-perusahaan ini, yang sebagian besar dimiliki oleh kaum borjuis Eropa, mulai mendominasi sektor ekonomi di wilayah jajahan.
Akibatnya, struktur penguasaan modal mengalami pergeseran signifikan, dengan kelas borjuis menjadi pilar utama kapitalisme dalam perusahaan-perusahaan tersebut.
Di tengah dinamika ini, Belanda memiliki alasan strategis untuk membentuk gemeente di Blitar, meskipun secara geografis daerah ini kecil dan relatif terisolasi.
Burgemeester Blitar, J.H. Boerstra, mengakui bahwa Blitar bukanlah daerah yang besar atau mudah diakses.
Namun, alasan-alasan strategis, seperti letaknya yang penting dan potensi ekonominya, menjawab pertanyaan mengapa Blitar dipilih sebagai gemeente.
Setelah berhasil membentuk Gemeente Blitar, Belanda menerapkan pengaturan yang lebih komprehensif.
Mereka menyediakan berbagai infrastruktur dan fasilitas penting, seperti kantor pemerintahan, stasiun kereta api, gardu induk listrik, gereja, taman kota, sekolah, rumah sakit, penataan kota, pembangunan jalan dan irigasi, serta simbol-simbol kota lainnya.
Fasilitas-fasilitas ini membawa perubahan signifikan pada kehidupan masyarakat setempat, memaksa mereka untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi kolonial, serta menciptakan kontak kultural antara kekuatan tradisional dan kolonial.
Industrialisasi di Blitar mencakup baik industri berbasis pedesaan maupun perkotaan.
Industri perkebunan berkembang pesat di Kabupaten Blitar, terutama di daerah subur seperti lereng Gunung Kelut dan lembah Brantas.
Pada awalnya, ratusan perkebunan berhasil dikembangkan oleh orang Eropa. Namun, pada tahun 1939, tercatat ada 45 perusahaan perkebunan yang menanam berbagai jenis tanaman seperti coffee, karet, kina, teh, tebu, tembakau, kapuk, singkong, dan kelapa.
Perusahaan-perusahaan ini memiliki unit pengolahan sendiri, baik di dalam kompleks perkebunan maupun di tempat lain. Hal ini memperkenalkan pola baru dan kemandirian dalam bertani kepada masyarakat lokal.
Perkebunan Coffee De Karanganjar merupakan salah satu contoh nyata dari perkembangan industri perkebunan di Blitar.
Didirikan pada tahun 1874 oleh Belanda, perkebunan ini menjadi saksi bisu sejarah industrialisasi di wilayah tersebut.
Namun, perjalanan De Karanganjar tidak selalu mulus. Pada tahun 1942, saat Jepang datang, kegiatan di perkebunan ini terhenti sementara waktu.
After Indonesia's independence, foreign companies were nationalised and management was handed over to veterans of the independence war.
Termasuk perkebunan Karanganjar, kemudian dikelola oleh veteran Denny Roeshadi, yang juga bekerja di perkebunan ini.
Untuk mendukung ekspor dan impor produk industri, Blitar telah dihubungkan dengan jaringan kereta api sejak tahun 1884 melalui rute Tulungagung-Kediri-Kertosono-Surabaya.
Pembangunan jalur kereta api ini merupakan bagian dari rencana besar pengembangan jaringan transportasi di wilayah jajahan.
Faktor alam dan finansial memainkan peran besar dalam proses industrialisasi di Blitar.
Masyarakat Blitar dan sekitarnya mengenal unen-unen yang menyebutkan Blitar dadi latar, Kediri dadi kali, Tulungagung dadi kedhung, yang sangat terkait dengan aktivitas Gunung Kelut di sebelah utara Blitar, di perbatasan dengan Kabupaten Kediri.
Ketiga daerah ini sering terdampak oleh letusan gunung. Salah satu letusan terbesar terjadi pada tahun 1919, menyebabkan 5.160 orang meninggal dan kerusakan hebat di Kabupaten Blitar dan Kediri.
Banjir lahar dari letusan ini menghancurkan lebih dari 15.000 hektar lahan pertanian dan perkebunan, serta meratakan ratusan desa dan kampung.
Jebolnya tanggul Sungai Badak menyebabkan Gemeente Blitar dilanda lahar hebat, menimbun sebagian besar kota dengan material vulkanik seperti pasir, batu, lumpur, kayu, kotoran, bangkai binatang, dan mayat manusia.
Dengan adanya industrialisasi dan perubahan struktural ini, Blitar mengalami transformasi besar-besaran.
Pengaruh kolonialisme dan kapitalisme membawa dampak yang mendalam terhadap masyarakat lokal, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya.