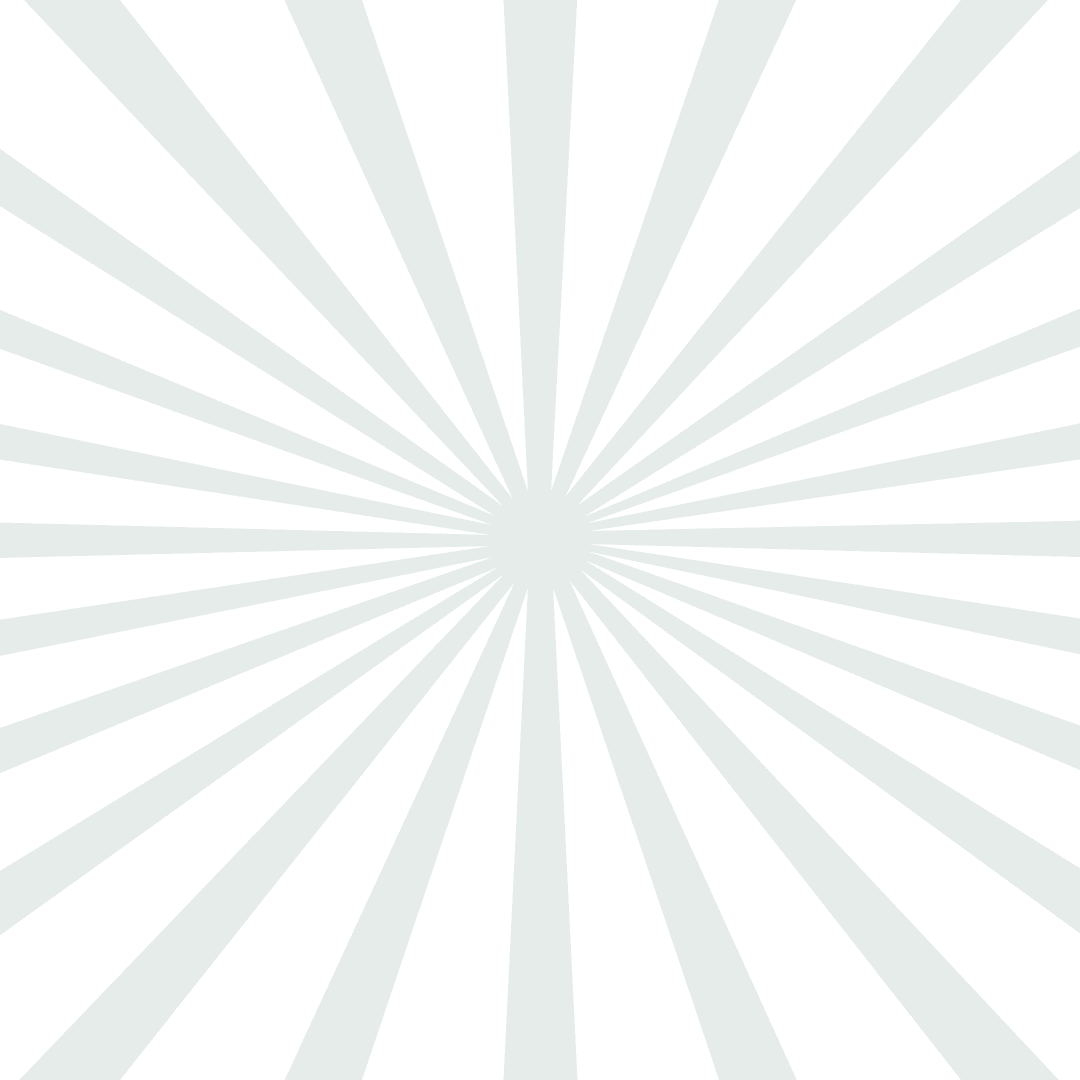Pada paruh kedua abad ke-19, situasi politik di Belanda ditandai dengan meningkatnya pengaruh kaum liberal.
Mereka bertujuan untuk mendapatkan kesempatan yang lebih besar dalam aktivitas dan pengelolaan ekonomi di wilayah jajahan.
Mereka percaya bahwa negara tidak mampu menangani semua masalah di wilayah jajahan yang begitu kompleks dan luas.
Oleh karena itu, mereka menginginkan kesempatan untuk berinvestasi modal mereka dalam berbagai usaha ekonomi di wilayah jajahan dan mengelola daerah tersebut sendiri agar dapat menangani dan menyelesaikan masalah yang timbul dengan efisien, sambil tetap memberikan keuntungan optimal bagi Belanda.
Konsep kapitalisasi di wilayah jajahan sesuai dengan perkembangan zaman.
Menurut Gunawan Wiradi, kaum liberal merasa cemburu karena hanya pemerintah yang memperoleh keuntungan besar melalui sistem tanam paksa, sementara pemodal yang memiliki kemampuan tidak mendapatkan kesempatan yang sama.
Mereka menuntut liberalisasi ekonomi di wilayah jajahan, yang berarti pemerintah kolonial tidak lagi menguasai sepenuhnya urusan ekonomi.
Mereka menginginkan ekonomi yang didasarkan pada undang-undang yang memberikan kesempatan kepada modal swasta untuk berinvestasi di bidang perkebunan dan usaha lainnya.
Tuntutan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, sehingga kelompok liberal berhasil memenangkan pertarungan politik di parlemen Belanda.
Kemenangan politik kaum liberal menghasilkan Undang-undang Agraria Kolonial dan Undang-undang Gula pada tahun 1870.
Kapital mereka semakin bertambah banyak, dan mereka mulai memikirkan perluasan usaha di wilayah jajahan.
Kepentingan ekonomi kaum borjuis mendukung gagasan liberalisme di Belanda.
Dalam bidang ekonomi, gagasan ini merupakan kritik terhadap peran negara dalam mengatur pasar, dan kaum borjuis menuntut penggantian sistem merkantilisme negara dengan korporasi swasta.
Penerapan undang-undang tersebut serta meningkatnya pengaruh liberalisme mendorong timbulnya perusahaan perkebunan dan pertambangan swasta besar di Jawa dan Sumatra.
Dampaknya, struktur kepemilikan modal mulai berubah dengan munculnya kelas borjuasi sebagai pemain utama dalam kapitalisme perusahaan perkebunan tersebut.
Kelompok ini semakin memperkuat basis modalnya dengan mengkonsentrasikan investasi dalam berbagai industri.
Di Blitar, perkebunan-perkebunan besar mulai dibuka, baik di sekitar lereng Gunung Kelut di Blitar Utara maupun di sepanjang lembah Sungai Brantas hingga daerah Blitar Selatan.
Usaha ini mengakibatkan peningkatan pengaruh Belanda dalam pengaturan dan eksploitasi wilayah Blitar, karena wilayah tersebut memiliki potensi ekonomi yang menguntungkan bagi mereka.
Investasi swasta di Blitar membantu memenuhi kebutuhan bahan mentah seperti karet, coffee, kakao, tebu, dan tembakau untuk pasar Eropa, serta kapas, serat nanas, kelapa, kina, teh, singkong, dan cengkeh.
Van den Bosch memperjuangkan pengembangan pertanian di Hindia Belanda dengan memberikan bimbingan dan bantuan sederhana kepada petani Jawa, agar mereka bisa mengelola usaha pertanian dengan lebih baik.
Melalui sistem Tanam Paksa, pemerintah menetapkan kewajiban bagi petani Jawa untuk menanam tanaman komersial pada sebagian tanah mereka dan mengirimkan hasilnya kepada pemerintah.
Para bupati dan pimpinan lokal diberi insentif untuk mendukung program Tanam Paksa ini, sehingga pemerintah tidak perlu menambah pegawai Belanda secara signifikan.
Van den Bosch juga berusaha meyakinkan raja bahwa produksi tanaman ekspor di Jawa bisa meningkat hingga 20 juta gulden setahun dengan mengoptimalkan produksi dan kerja sama dengan penguasa lokal.
Selanjutnya, pertanian swasta berkembang pesat di Hindia Belanda, terutama di Kabupaten Blitar, dengan usaha perkebunan yang berhasil memberikan keuntungan besar bagi pemerintah dan berdampak positif pada perkembangan Kota Blitar.
Salah satu contoh adalah estate coffee Karanganjar, Blitar, yang masih eksis hingga saat ini bahkan menjadi salah satu daya tarik pariwisata Blitar.